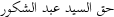Pada sebuah pertemuan jaringan kaum muda NU di Pesantren “Ribatul Muta’allimin” Pekalongan pada awal tahun 2000, disepakati untuk mengusung isu “Tragedi 1965”. Sejak itu mulai dilakukan diskusi-diskusi, dan merancang strategi untuk menggarap isu sensitif ini. Dikatakan sensitif karena di dalam sejarahnya, keterlibatan kelompok Islam dan khususnya Nahlatul Ulama dalam proses pembasmian (orang-orang) komunis di Indonesia, sangatlah masyhur dan tak bisa ditutup-tutupi. Gus Dur ketika menjadi presiden pernah melontarkan permintaan maafnya, lebih dalam kapasitasnya sebagai orang NU yang mempunyai beban sejarah yang sangat berat, kepada orang-orang yang selama ini mengalami penderitaan karena dituduh terlibat pemberontakan komunis. Pengakuan dan pernyataan Gus Dur ini membuka peluang yang cukup besar bagi masuknya isu tragedi 1965 ini ke dalam wacana Islam, paling tidak telah membuka hal-hal yang selama ini “tabu” dibicarakan menjadi “layak” dibicarakan dan diperdebatkan.
Di samping itu isu kemanusiaan akibat krisis ekonomi yang membuka tabir kepalsuan “pembangunan ekonomi”, secara tidak langsung membuka kemungkinan pengungkapan fakta kemiskinan yang diderita oleh keluarga korban tragedi 1965 sebagai akibat perampasan hak-hak mereka, stigmatisasi dan diskriminasi.
Sedikit “peluang” ini tentu saja tidak harus mengabaikan “tantangan” yang mungkin dihadapi. Tantangan itu merupakan dampak indoktrinasi orde baru atas pikiran masyarakat Indonesia pada umumnya tetap memperoleh pengesahannya di dalam masyarakat Islam. Pertama, bahwa ‘atheisme’ merupakan sesuatu yang dilekatkan pada PKI. Ini akan menjadi pusat serangan yang ‘mematikan’ bagi gerakan rekonsiliasi, di mana pemrakarsa maupun aktivis yang mengusung rekonsiliasi akan mudah dicap sebagai ‘membantu bangkitnya komunisme’ lagi. Kedua, PKI merupakan dalang dari G30S sebagaimana yang digambarkan oleh ‘Buku Putih’ versi pemerintah, sehingga penumpasan dan pembasmian komunisme baik melalui pembunuhan, pemenjaraan, pelarangan ideologi komunisme/marxisme/leninisme merupakan sesuatu yang ‘seharusnya’ dilakukan. Mempertanyakan ‘keabsahan’ tindakan rejim orde baru itu bagi usaha rekonsiliasi akan menjadi ‘tuduhan’ kepada pemrakarsa maupun aktivisnya sebagai upaya ‘mensucikan PKI’ dan mempersetankan militer dan para pendukungnya.
Dari peluang dan tantangan itulah kami merumuskan strategi untuk upaya rekonsiliasi. Secara umum strategi itu dirumuskan dalam kalimat ‘rekonsiliasi akar rumput’ yang menggunakan pendekataan kemanusiaan dan bersifat kultural (termasuk dengan pendekatan keagamaan).
Pertama, strategi pokok yang diusung sebagai titik masuk dalam program rekonsiliasi adalah mengusung isu kemanusiaan. Hal ini mengandaikan, bahwa siapa pun juga, dari latar belakang keyakinan maupun agama apapun, (diharapkan) akan menghormati hak-hak paling dasar manusia, seperti hak hidup dasariahnya, katakanlah – meskipun manusia mempunyai kesalahan pada masa lalu. Panggilan keagamaan bahkan mengharuskan memberdayakan orang-orang yang telah dianiaya, dan berkewajiban membantu mengembalikan hak-hak mereka yang telah dirampas. Pendekatan ini diharapkan bisa membuka mata hati masyarakat Islam yang selama ini ‘memusuhi’ para korban atas dasar pembenaran ideologis. Namun mengubah pandangan ideologis menjadi pandangan kemanusiaan, bukanlah hal mudah. Oleh karena itu, diperlukan tindakan strategis dan taktis untuk mengubah pandangan ini.
Kedua, strategi mengungkapkan kebenaran dari bawah. Maksudnya, narasi masa lalu yang dijadikan indoktrinasi oleh rejim orde baru adalah ‘narasi pusat’, dengan setting lokasi maupun konflik tingkat elit. Sementara konflik elit seperti itu ‘susah dipahami’, namun korban dari konflik itu justru terjadi di kalangan orang biasa secara geografis maupun politis jauh dari Jakarta. Oleh karena itu, pendekatan lokalitas yang mencoba mengungkapkan ‘narasi kecil’ sangat strategis untuk membalik ‘ingatan ciptaan elit’ yang tak tersentuh, menjadi sesuatu yang ‘nyata’, sebagaimana peristiwa tragis 1965 itu dialami oleh orang-perorang, dalam basis keluarga, dalam lokasi dan waktu yang sangat akrab dan ‘dilakoni’ dengan segenap jiwa para korban.
Ketiga, melihat tragedi 1965 dari perspektif perempuan. Sebagaimana diketahui, tragedi 1965 telah menempatkan perempuan dan gerakan perempuan sebagai salah satu ‘tertuduh’ sedemikian rupa, yang menguatkan aroma kebencian terhadap komunisme menjadi sangat pekat. Stigma yang dilekatkan kepada Gerwani, sebagai perempuan-perempuan jahat yang menggunakan seksualitasnya untuk menjadikan drama penculikan ‘para pahlawan revolusi’ penuh kekejian, amoral. Sebaliknya, penghukuman terhadap perempuan pun menggambarkan sebuah proses balas dendam yang ‘setimpal’. Akibatnya, perempuan yang menjadi korban mengalami trauma yang mendalam, sementara citra buruk yang terus dilekatkan kepada mereka membuat mereka tersisih, terbungkam suaranya dan cenderung diabaikan dalam proses rekonsiliasi.
Strategi yang dipilih memang bersifat sosial dan kultural, tentu dengan memahami bahwa masalahnya tidak semata-mata sosial dan kultural, melainkan juga politik. Pilihan sosio-kultural yang dialami oleh para korban bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan politik. Hambatan politik yang sangat besar, seandainya bisa dipatahkan, tetapi masalah sosio-kulturalnya tetap sulit dipecahkan. Dengan kata lain, stigma dan derita yang dialami para korban tidak hanya diproduksi oleh “rejim” politik, tetapi bahkan telah diproduksi oleh kelompok-kelompok sipil lainnya sebagai hasil dari proses “rekayasa ingatan” yang sistematik. Hingga saat ini masih selalu muncul spanduk-spanduk “Waspadai Komunisme” yang dibuat atas nama Front Anti Komunis, Gerakan Anti Komunisme Baru yang muncul di mana-mana.
Dengan demikian gerakan awal untuk rekonsiliasi menempatkan proses “penyembuhan” stigma dan trauma sebagai prioritas program ini. Tahap-tahap program “Rekonsiliasi Akar Rumput” ini mencakup tahap persiapan yang dibagi menjadi dua arah; (1)persiapan sosial dan ke (2)persiapan kelembagaan.
Mempersiapkan Payung Sosial
Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan stakeholder utama gerakan ini, dalam hal ini adalah komunitas Islam, untuk siap menerima argumen-argumen strategi kemanusiaan yang digunakan dalam program rekonsiliasi ini. Dalam hal ini, pendekatan kepada key persons baik para tokoh Ulama dan pimpinan organisasi Islam dilakukan.
Ketika program ini telah disepakati untuk dikerjakan pada akhir tahun 2000, pendekatan dan sosialisasi kepada para Ulama dimulai. Kami mengidentifikasi kunci-kunci “password” di semua daerah yang akan dijadikan “eksperimentasi” program ini. Sebagaimana diketahui, di dalam komunitas Islam dan pesantren terdapat hirarki yang cukup rumit untuk dipahami, namun harus dilakukan supaya program ini “tepat sasaran”. Di dalam hirarki ini para Ulama kunci diprioritaskan, dan dari sini ulama lingkar kedua bisa didekati dengan mudah. Ulama kunci dalam hirarki Nahdlatul Ulama secara struktural adalah Rois Am, yakni ketua dari dewan ulama yang menjadi penentu organisasi. Di samping ulama-ulama yang berada di dalam hirarki kepengurusan NU, terdapat “Ulama kultural” yang tak bisa diabaikan pengaruhnya di dalam umat.
Dalam tradisi pesantren, orang muda menghormati orang tua. Santri menghormati kiainya. Dan begitulah sosialisasi program dilakukan dengan cara bertatap muka, satu persatu dengan para kiai. Pada umumnya, para kiai dari kedua jalur hirarki tersebut mendukung program ini. Meskipun ada catatan-catatan yang harus kami perhatikan, tetapi ‘legitimasi’ dari mereka sangat bermanfaat di kemudian hari.
Di sisi lain, pendekatan juga dilakukan dengan para tokoh ‘eks tapol’ yang pasca Suharto telah menginisiasi berbagai organisasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Misalnya, kami bertemu dan berbicara dengan ibu Sulami, ketika itu beliau ketua YPKP 1965-66 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-66), Hasan Raid, Yusuf Suwaji, Ibu Putmainnah (Blitar, mantan Gerwani), dll. YPKP sebagai organisasi korban tragedi 1965-66 waktu itu merupakan organisasi yang cukup solid, dengan cabang-cabangnya telah berdiri merata di Jawa, Bali, dsb. Organisasi ini sangat membantu untuk membuka ‘kunci’ password di daerah-daerah yang akan menjadi tempat penelitian dan ‘eksperimentasi’ rekonsiliasi akar rumput. Selain itu terpdaka LPRKrob, Pakorba, LPKP (pecahan YPKP), dll. Pendekatan terhadap organisasi para korban ini tentu saja sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan, sehingga para korban nantinya bersedia mengungkapkan kisah-kisahnya dan bersama-sama bergerak memperjuangkan hak-hak sosial dan politiknya.
Penyiapan institusi
Tahap ini sangat penting untuk mempersiapkan model organisasi apa yang akan digunakan, siapa saja ‘operatornya’ dan bagaimana cara menjalankan organisasi itu. Tentu saja model organisasi tunggal untuk menangani program ini tidak akan memadahi, tetapi harus dicari model jaringan (network) dan jejaring (network of networks). Organisasi berbasis pesantren dan Nahdlatul Ulama yang telah memperoleh latihan dan wawasan mengenai hak asasi manusia dan demokrasi didorong untuk mampu secara kapasitas maupun sumberdayanya. Mereka inilah yang kemudian mendirikan organisasi jaringan bernama Syarikat Indonesia (SI), akronim dari Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat Indonesia. SI menjadi ‘sekretariat’ atau focal point yang mengelola program ini, baik dari segi manajemen gerakan maupun mencari sumber dana yang diperlukan bagi program ini. Sedangkan organisasi yang mendukungnya menjadi perumus garis besar program dan sekaligus sebagai implementator di lapangan. Permusyawaratan tertinggi ada di tangan organisasi pendukung. Sedangkan untuk sehari-hari, SI dikelola oleh sebuah badan eksekutif yang terdiri dari Koordinator, Sekretaris dan Bendahara, dan dilengkapi program officer bidang penelitian, media dan advokasi. Organisasi pendukung dan anggota jaringan semula hanya 18 kota, tetapi kemudian berkembang lebih dari 30 kota di Jawa dan luar Jawa.